Beni menarik napas panjang. Hatinya teriris melihat kekasihnya menderita seperti ini. Ia lebih merengkuh Cecil ke dalam pelukannya. Ia tahu Cecil sangat butuh kenyamanan. Paling tidak, ia tidak boleh menderita terlalu jauh lagi.
“Sebentar lagi kita sampai di Stasiun Gambir, Sayang.” Beni berharap kata-katanya bisa menghibur Cecil.
Dua puluh menit berlalu, taksi yang mereka naiki sudah sampai di depan Stasiun Gambir. Beni turun lebih dulu dan membiarkan Cecil masih terduduk di jok penumpang. Sepuluh menit kemudian, Beni kembali menjemput Cecil.
“Aku udah dapat tiketnya, Sayang. Keretanya satu jam lagi.”
Cecil tersenyum. Beni melihatnya. Ia tahu, gadisnya mengeluarkan banyak tenaga untuk sekadar tersenyum seperti itu. Setelah menyelesaikan pembayaran taksi, perlahan Beni membantu Cecil keluar dari taksi. Sang supir taksi rupanya seorang yang sigap. Tadi ia berlari ke lobi untuk mengambil kursi roda.
“Pakai ini aja, Mas,” ujarnya pada Beni.
“Nggak,” suara lirih Cecil lebih dulu terdengar.
“Kamu yakin, Sayang? Perjalanan ke peron bakal kerasa jauh sekali buatmu.”
“Nggak apa-apa. Aku sanggup, kok, Ben.”
Beni melihat ke arah supir taksi, seolah-olah mengucap maaf dengan pandangan matanya. Sang supir pun sudah mengerti.
“Nggak apa-apa, Mas. Nanti saya kembalikan lagi ke tempatnya.”
Ben mengangguk. Ia berjalan pelan sambil memapah Cecil.
Perlu waktu hampir tiga puluh menit untuk menuju peron di lantai tiga. Beni langsung menuju sebuah bangku yang terletak tak jauh dari tangga, juga bersebelahan dengan salah satu pilar besar penyangga atap. Ia dudukkan Cecil di sana, kemudian merapatkan kardigan warna marun yang membungkus tubuh kurus gadis itu. Setelah itu, Beni menempatkan diri di sisi gadis yang baru bulan lalu menjadi tunangannya.
“Ben, masih lama, ya?”




















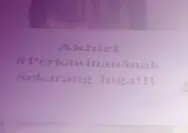






Artikel Terkait
Guru Berdaster
Kita Membutuhkan Kata Saling
PUISI: Aku Akan Menangis Lain Kali
PUISI: Rembulan Menangis
CERPEN: Pertemuan Kedua
PUISI: Sekisah Cappucino
Puisi Cevi Whiesa Manunggaling Hurip.
PUISI: Melukis dalam Doa dan Harapan