KLIKANGGARAN -- Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran atau FITRA, mengkritisi nota keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jum’at, 15 Agustus 2025. FITRA menilai bahwa kutipan yang dibacakan belum mencerminkan kondisi dan realitas masyarakat yang sebenarnya.
Sekretaris Jendral FITRA, Misbah Hasan, memberikan beberapa catatan kritis:
1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Cenderung “Pencitraan” dan Tidak Melihat Realitas Masyarakat.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi tiga tahun sebelum pandemi (2017-2019) hanya 5,09% (yoy) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiga tahun pasca pandemi (2022-2024) hanya 5,13% (yoy)[1]. Sementara proyeksi di 2026 ditetapkan mencapai 5,4%. Jelas ini optimisme yang berlebih alias pencitraan. Meski pada Triwulan II pertumbuhan ekonomi Indonesia ‘diclaim’ oleh pemerintah mencapai 5,12% dan menimbulkan polemik data di kalangan ahli. Penetapan 5,4% pertumbuhan ekonomi tentu membutuhkan efford luar biasa, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak baik-baik saja, perang tarif antar negara, dan daya beli masyarakat yang belum stabil. Tingkat konsumsi Rumah Tangga relatif stagnan dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) di angka 4,87%, sementara program-program Perlindungan Sosial – seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, berbagai Subsidi, yang selama ini menopang daya beli masyarakat masih banyak salah sasaran.
2. Reformasi Perpajakan belum Komperehensif hingga Daerah sehingga Membebani Rakyat Kecil.
Pendapatan Negara pada 2026 ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dimana penerimaan terbesar masih dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp2.692 triliun atau 85,5%. Naik 11,3% dibanding Outlook APBN 2025. Terbesar kedua adalah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp455 triliun atau 14,5% dari total Pendapatan Negara atau turun 4,8% dibanding Outlook PNBP 2025. Yang menjadi persoalan hingga saat ini Adalah: (1) Sistem Pelayanan Perpajakan (Coretax) belum stabil sehingga belum ada ‘trust’ dari masyarakat; (2) Lemahnya integrasi sistem penerimaan negara (pajak, bea-cukai, dan PNBP) sehingga dan akurasi data penerimaan rendah dan kualitas pengawasan lemah; (3) Lemahnya kualitas pemeriksaan, sehingga menimbulkan sengketa perpajakan yang tinggi; (4) Fragmentasi pusat dan daerah pasca ditetapkannya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Contohnya adalah belum sinkronnya desain pajak dan tata kelola implementasi Opsen Pajak dan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini menimbulkan ‘kesewenang-wenengan’ Pemerintah Daerah menaikan pajak/retribusi. Kasus terbaru di Kabupaten Pati yang kemungkinan akan terjadi di daerah-daerah lain; (5) Minimnya transparansi dan akuntabilitas Belanja Perpajakan (Tax Expenditure) yang diestimasi mencapai Rp563,6 triliun. Belanja Perpajakan ini 50%-nya besar berasal dari PPN dan PPnBM, dan paling banyak digunakan untuk sektor Industri Pengolahan (25%). Sedangkan untuk Air Minum, Penangan Sampah, dan Sanitasi hanya 11%, Jasa Pendidikan (0,5%), dan Jasa Kesehatan (5%).
3. Potensi Resentralisasi Belanja Negara dan ‘Distrust’ kepada Daerah Semakin Nyata.
Hal ini terlihat dari postur Belanja pada RAPBN 2026. Dari total Belanja Negara yang ditetapkan sebesar Rp3.876,5 triliun, 83% dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat atau sebesar Rp3.136,5 triliun. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) hanya mendapat jatah Rp650 triliun atau 17% dari total Belanja Negara, turun drastis dibanding TKD 2025 yang sebesar Rp919,9 triliun dan Outlook APBN 2025 Rp864,1 triliun.
Ada kecenderungan alokasi anggaran ‘dikuasai’ oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah K/L yang gemuk atau terjadi resentralisasi keungan negara. Sementara Daerah hanya dikasih ‘remah-remah’ dengan berbagai earmark yang menyertainya. Earmaking TKD adalah Transfer Keuangan Pusat ke Daerah yang sudah ditentukan penggunaannya, sehingga daerah kesulitan mengalokasikan untuk prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing. Ini artinya, Daerah tidak lagi dipercaya oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola anggaran negara untuk pencapaian pembangunan.
4. Program-program Direktif Presiden menyedot dana besar, tanpa studi kelayakan, tanpa partisipasi publik, sehingg sangat riskan diselewengkan.
Program seperti Ketahanan Pangan menyedot anggaran Rp164,6 triliun, Ketahanan Energi Rp402,4 triliun, MBG Rp335 triliun, Pendidikan termasuk Sekolah Rakyat Rp757,8 triliun, Kesehatan – termasuk Cek Kesehatan Gratis Rp244 triliun, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya 80.000 Koperasi akan berhutang ke Bank Himbara sekitar Rp400 triliun dan bila rugi akan ditanggung APBDesa, Pertahanan Semesta, 3 Juta Rumah, dll.
Sebagian besar program-program tersebut bersifat top down dan tanpa background study yang memadai dan komperehensif, sehingga dampaknya akan sangat kecil dirasakan oleh masyarakat. Dalam studi yang dilakukan TII terkait Program MBG misalnya[2], ditemukan potensi korupsi sistemik, mulai dari regulasi yang belum kuat, penunjukan mitra pelaksana Satuan Pelayananpemenuhan Gizi (SPPG) tidak terbuka, lemahnya koordinasi antar sektor, dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) yang tidak transparan. Sehingga anggaran MBG yang sangat besar hanya dijadikan ajang bancakan.
Kesimpulan dan Rekomendasi


























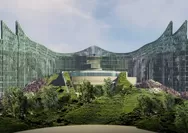
Artikel Terkait
Airlangga: Prabowo Berperan Turunkan Tarif Ekspor RI ke AS Usai Kontak Trump
Bank Nasional dan Daerah Tegaskan Dana Nasabah Aman di Tengah Penataan Rekening Dormant, dari BRI, Mandiri hingga Bank Kalbar
Pemerintah Siapkan SKB Libur Nasional 18 Agustus 2025, Pengumuman Resmi Direncanakan Rabu Ini
Nusron Wahid: Proses Penetapan Tanah Terlantar Butuh 587 Hari, Negara Tak Bisa Langsung Ambil Alih
Menkumham Supratman Tegaskan Royalti Bukan Pajak, Negara Tak Dapat Keuntungan dari Kasus di Bali
143 Guru Mengundurkan Diri dari Sekolah Rakyat, Mensos Saifullah Yusuf Pastikan Pengganti Sudah Disiapkan dan Siap Mengajar
OJK Rilis Pedoman Keamanan Siber Kripto, Terapkan Prinsip Zero Trust untuk Lindungi Ekosistem Perdagangan Aset Digital
Pramono Anung Tegaskan Kenaikan PBB Jakarta Maksimal 10 Persen, Properti di Bawah Batas NJOP Tetap Bebas Pajak
Mendagri Tito Karnavian Tanggapi PBB Naik: Hanya Bisa Intervensi, Tidak Punya Wewenang Membatalkan Kebijakan Daerah
Utang BLBI BCA Jadi Sorotan: Saham Dilepas Rp10 Triliun, Negara Disebut Rugi Rp78 Triliun menurut Kwik Kian Gie